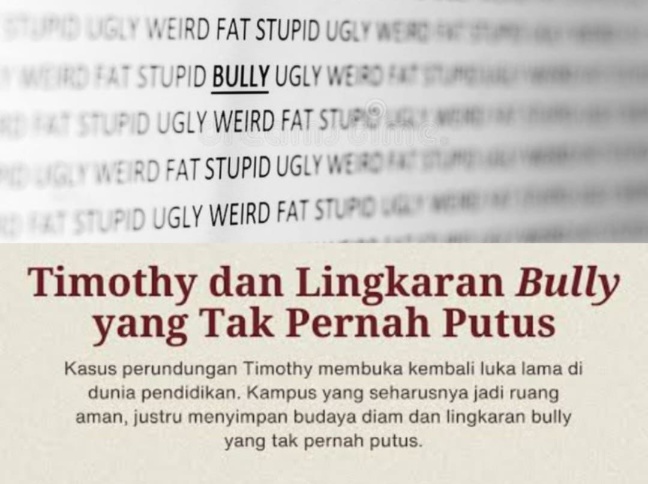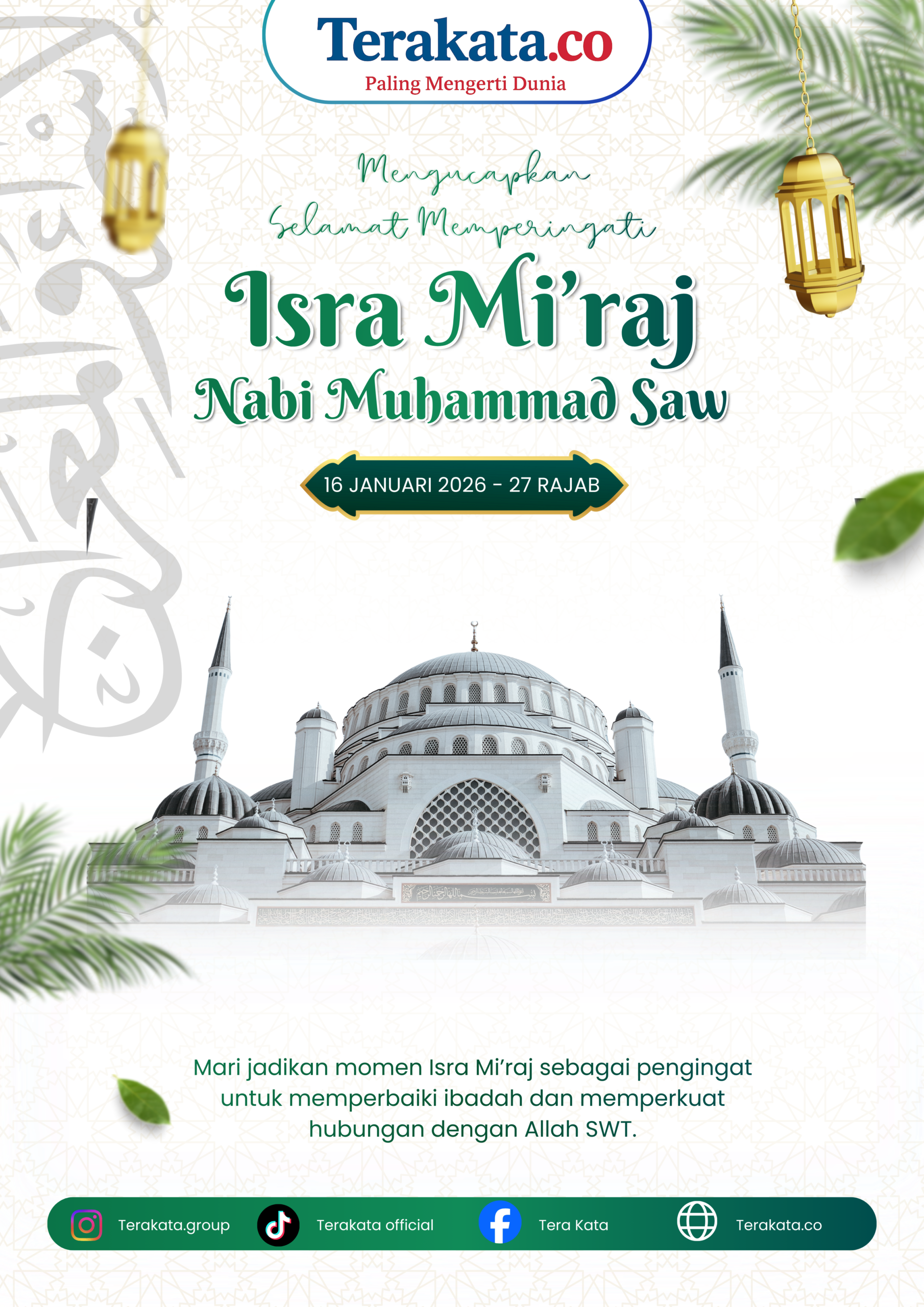Tidak semua luka berdarah. Sebagian justru hadir dalam diam, tersembunyi di balik layar ponsel dan deretan pesan singkat yang dikirim tanpa pikir panjang. Di ruang digital yang seharusnya menjadi tempat berbagi dan saling menguatkan, cyber bullying tumbuh sebagai kekerasan yang sering kali luput dari perhatian hingga suatu hari, ia menyisakan kehilangan yang tak tergantikan.
Tragedi meninggalnya Timothy Anugerah Saputera, mahasiswa Universitas Udayana, membuka kembali luka kolektif tentang betapa rapuhnya manusia di tengah hiruk-pikuk dunia digital.
Timothy pergi di usia 22 tahun, meninggalkan duka bagi keluarga dan tanda tanya bagi publik. Namun, yang paling menyayat bukan hanya peristiwa kepergiannya, melainkan respons sebagian orang di ruang digital yang justru kehilangan empati.
Ketika kabar Timothy tersebar, percakapan di grup WhatsApp mahasiswa yang kemudian viral memperlihatkan sisi gelap kebebasan berekspresi.
Alih-alih belasungkawa, muncul olok-olok dan candaan yang merendahkan. Meski pihak kampus menegaskan bahwa percakapan itu terjadi setelah Timothy meninggal dan tidak menjadi penyebab langsung tragedi, tetap ada luka yang tercipta. Luka bagi keluarga yang berduka, dan luka bagi kita semua yang menyadari betapa mudahnya empati menghilang di balik layar.
Cyber bullying tidak selalu datang dalam bentuk ancaman terang-terangan. Ia kerap hadir sebagai candaan, komentar sinis, atau sikap nir-empati yang dianggap wajar.
Padahal, bagi korban dan orang-orang terdekatnya, kata-kata itu bisa menjadi beban berat. Dunia digital tidak mengenal jeda emosi; sekali terkirim, pesan dapat menyebar luas dan menetap lama.
Sebagai pemuda, kita berada di garis depan ruang digital. Kita yang paling sering bersuara, berbagi, dan bereaksi. Namun, di situlah tanggung jawab itu melekat.
Bagi kita sebagai perempuan, peran ini terasa lebih personal. Perempuan kerap dibesarkan dengan kepekaan emosional, kemampuan merawat, dan empati nilai-nilai yang sering diremehkan, tetapi justru sangat dibutuhkan di tengah kerasnya ruang digital hari ini.
Menjadi perempuan muda di era digital bukan hanya soal eksistensi, tetapi juga soal keberanian memilih sikap. Berani tidak ikut menertawakan, berani menghentikan percakapan yang merendahkan, dan berani berdiri di sisi kemanusiaan ketika mayoritas memilih diam.
Empati bukan tanda kelemahan; ia adalah bentuk kekuatan moral yang sering kali paling sunyi, namun paling berdampak.
Dari kisah ini, ada nilai-nilai penting yang patut direnungkan. Bahwa kebebasan berekspresi selalu berdampingan dengan tanggung jawab. Bahwa jabatan, status organisasi, atau kecerdasan akademik tidak otomatis melahirkan kedewasaan emosional. Dan bahwa diam di hadapan perundungan sering kali berarti ikut membiarkannya terjadi.
Sebagai pembaca, mungkin kita tidak pernah mengenal Timothy secara pribadi. Namun, perasaannya bukanlah sesuatu yang asing. Siapa pun pernah berada di titik rapuh merasa sendiri, disalahpahami, atau lelah menghadapi dunia. Di situlah artikel ini mengajak kita berhenti sejenak, bercermin, dan bertanya: sudahkah kita cukup berhati-hati dengan kata-kata kita? Sudahkah kita hadir sebagai manusia, bukan sekadar pengguna media sosial?
Apa yang Bisa Kita Lakukan sebagai Pemuda?
Menghadapi cyber bullying tidak selalu membutuhkan langkah besar atau posisi
berkuasa. Justru perubahan paling bermakna sering lahir dari tindakan-tindakan kecil yang konsisten. Sebagai pemuda, ada beberapa solusi nyata yang bisa kita
lakukan.
Pertama, menjadi pengguna media sosial yang berempati. Berpikir sebelum mengetik adalah langkah paling sederhana sekaligus paling penting. Bertanya pada diri sendiri: apakah kata-kata ini perlu? Apakah ini bisa melukai orang lain? Kesadaran ini dapat mencegah banyak luka sebelum terjadi.
Kedua, berani menghentikan rantai perundungan. Tidak ikut menertawakan, tidak menyebarkan ulang konten yang merendahkan, dan berani menegur dengan cara yang bijak ketika melihat perilaku nir-empati. Diam sering kali dianggap aman, tetapi keberanian untuk bersuara justru dapat menyelamatkan seseorang dari rasa terisolasi.
Ketiga, menjadi ruang aman bagi sesama. Mendengarkan tanpa menghakimi, memberi dukungan, dan mengarahkan korban untuk mencari bantuan profesional atau melapor ke pihak berwenang adalah bentuk kepedulian yang sangat berarti. Kadang, seseorang hanya butuh tahu bahwa ia tidak sendirian.
Keempat, menguatkan literasi digital dan kesehatan mental. Pemuda bisa berperan
sebagai agen edukasi baik melalui diskusi kecil, komunitas, maupun konten positif di media sosial. Menormalkan pembicaraan tentang kesehatan mental dan empati
adalah langkah penting untuk mematahkan stigma.
Kelima, menghidupkan nilai kemanusiaan dalam organisasi dan komunitas. Bagi pemuda yang tergabung dalam organisasi kampus atau komunitas sosial, penting untuk menegakkan etika komunikasi dan menolak segala bentuk kekerasan verbal.
Kepemimpinan sejati bukan soal kuasa, melainkan tanggung jawab untuk melindungi.
Solusi terhadap cyber bullying tidak hanya terletak pada aturan dan sanksi, tetapi pada keberanian individu untuk bersikap manusiawi di tengah arus digital yang sering kali dingin dan tanpa wajah.Tragedi ini seharusnya tidak berhenti sebagai berita yang perlahan dilupakan.
Ia adalah pengingat bahwa ruang digital dan ruang akademik harus tetap manusiawi. Bahwa di balik setiap komentar ada hati yang bisa terluka, dan di balik setiap unggahan ada tanggung jawab moral.
Pada akhirnya, cyber bullying adalah luka sunyi yang hanya bisa disembuhkan dengan empati yang nyata. Dan sebagai generasi muda terutama kita sebagai perempuan kita punya pilihan: membiarkan luka itu terus menganga, atau menjadi bagian dari proses penyembuhannya.
Oleh: Nesya Dwi Febrianti (C1D323109), Risda Mayanti (C1D323119), Tiwi Kumalasari (C1D323133), Wa Ode Marsanda (C1D323135).
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Program Studi Jurnalistik Universitas Halu Oleo Kendari 2025.
Penulis: Red
Editor: Aman